Mind Map
A.
Struktur Sosial
Struktur
secara harfiah berasal dari kata structum yang artinya menysusun,
membangun, konstruksi atau kerangka yang menjadi susunan suatu bangunan.
Misalnya, dalam sebuah bagunan terdapat fondasi, lantai, tiang, atap dan
tembok. Lebih sepesifik dalam bangunan terdapat pintu, jendela, ventilasi,
saluran air, sanitasi, instalasi listrik dan lain sebagainnya. Dapat
dibayangkan, jika bangunan tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka bangunan
tersebut masih kurang layak untuk ditempati atau digunakan oleh manusia. Sama halnya dengan
bangunan, masyarakat juga memiliki suatu struktur, karena setiap manusia yang ada di dalamnya memilik peran, dan status yang berbeda-beda. Keberagaman manusia itulah yang menyebabkan kehidupan ini menjadi dinamis, berkembang, dan memiliki berbagai macam fungsi. Sebenarnya seluruh manusia yang ada di dunia ini telah menempati posisi dalam struktur atau kerangka-kerangka pembentuk dimensi sosial. Sebagai contoh, ketika manusia dilahirkan sebagai
anak pertama, status dan peran orang tua pun akan berubah menjadi ayah dan ibu. Sebutan ayah dan ibu bukan hanya sebagai simbol penanda sosial saja, melainkan memiliki berbagai macam fungsi dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan si anak dan kemajuan keluarganya. Pada akhirnya peran dan status yang dijalankan dalam keluarga tersebut akan berpengaruh pada struktur yang lebih luas, yaitu struktur dalam masyarakat.
Ada
dua pendekatan utama yang bisa dikemukakan untuk menjelaskan struktur sosial. Pendekatan
yang pertama membayangkan struktur sosial sebagai pola-pola yang dapat dilihat
dalam praktik sosial. Sebuah contoh dari pendekatan ini adalah fungsionalisme
(Functionalism). Pendekatan kedua mendapati struktur sosial berada di dalam
prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial, yang mungkin tidak terlihat.
Sebuah contoh dari pendekatan ini adalah realisme (Realism).
Secara
umum struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan yang terus bertahan,
teratur dan terpola di antara unsur-unsur masyarakat, sebuah definisi yang
mendorong beberapa ahli sosiologi abad ke-19 untuk membandingkan masyarakat
dengan mesin atau makhluk hidup lainnya. Ada sejumlah pembantahan atas apa yang
dijelaskan sebagai “unsur”. Radcliffe-Brown, misalnya, membayangkan
struktur sosial sebagai hubungan antar
orang yang umum dan teratur. S.F Nadel, di sisi lain, menyarankan peran sebagai
unsur-sosial. Bahkan yang lebih umum, insitusi sosial sebagai pola-pola
perilaku sosial yang terorganisasi, diusulkan sebagai unsur struktur sosial
sosial oleh para ahli sosiologi yang kemudian mendefinisikan masyarakat dari
sudut pandang hubungan fungsional di antara lembaga-lembaga sosial. Bagi mereka
unsur-unsur sosial tertentu (lembaga sosial) sangatlah penting karena merupakan
prasyarat fungsional.
Struktur
sosial digunakan untuk memehami perilaku manusia, karena struktur merupakan kerangka
masyarakat yang sudah terbentang sebelum kita dilahirkan. Struktur sosial
merujuk pada pola khas suatu kelompok, seperti hubungan yang lazim, seperti
antara kaum laki-laki dan perempuan, atau antara guru dan siswa. Sosiologi melihat struktur sosial sebagai
pemandu perilaku manusia di masyarakat.
Berikut penjelasan para ilmuan sosial mengenai struktur
sosial:
1.
Soerjono
Soekanto
Struktur
sosial adalah hubungan timbal balik antarposisi sosial dan peran sosial
2.
Nasikun
Dalam
konteks Indonesia struktur social dapat dilihat secara horizontal maupun
vertical Secara horizontal struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan
sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa,agama , adat, ras.yang disebut dengan
differensiasi sosial Secara vertikal struktur sosial ditandai ditandai adanya
kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan –lapisan sosial yang disebut
dengan stratifikasi sosial
3.
Radclife-Brown
Struktur
sosial merupakan rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud
dalam suatu masyarakat. Struktur sosial meliputi relasi sosial di anatara
individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peran sosial mereka
4.
George c.
Homans
Struktur
sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar
dalam kehidupan sehari-hari
5.
Raymond Flirth
Struktur
sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok
yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga dimana orang
banyak tersebut ambil bagian
B.
Elemen dasar pembentuk Struktur Sosial
1.
Status (kedudukan/posisi
seseorang dalam masyaratkat).
a. Assigned status (diberikan)
Status yang diberikan kepada seseorang karena
telah berjasa melakukan sesuatu untuk masyarakat, misalnya pahlawan nasional.
b. Ascribed status (dibebankan “otomatis”)
Status atau kedudukan yang diperoleh secara
otomatis (warisan/keturunan) tanpa usaha, misalnya jenis kelamin, marga,
klan, suku dan ras.
c. Achieved status (diperjuangkan)
Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha
sendiri atau sengaja diperoleh. Status yang harus diperjuangkan dan harus
menempuh kualifikasi tertentu untuk mendapatkannya. Misalnya jika seseorang
ingin mendapat gelar sarjana maka orang tersebut harus menempuh jenjang S1 di
universitas.
2.
Peran (hak dan kewajiban sesuai
dengan statusnya).
Merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan
individu yang telah berhasil menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan
kedudukannya (statusnya), berarti individu tersebut berhasil melakukan perannya
3.
Kelompok
Kelompok
memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam struktur sosial masyarakat
karena sebagian besar interaksi sosial kita berlangsung dalam kelompok dan
dipengaruhi oleh norma-norma dan sanksi yang ada dalam kelompok. Kelompok
sosial merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan
harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi.
4.
Institusi/lembaga
Merupakan
pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan kebutuhan
dasar sosial. Institusi dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Melalui institusi sosial, terlihat struktur dalam masyarakat. Institusi sosial
seperti keluarga, agama, dan pemerintah merupakan aspek fundamental dari
struktur sosial.
C.
Jenis Struktur Sosial
1.
Interseksi
(Menyilang)
Yaitu persilangan / pertemuan/ titik potong
kenggotaan anggota – anggota dari dua suku bangsa atau lebih dalam kelompok
sosial di dalam suatu masyarakat yang majemuk Contoh : Abdullah dari Aceh ,
Slamet dari jawa, Dadang dari Sunda bertemu bersama – sama dalam organisasi
Islam
 |
| Interseksi |
2.
Konsolidasi
(Penguatan identitas)
Yaitu penguatan atau peneguhan keanggotaan anggota –
anggota masyarakat dalam kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan. Contoh
:
 |
| Konsolidasi |
D.
Bentuk Struktur Sosial
1. Diferensiasi
sosial
Pembedaan anggota
masyarakat dalam golongan – golongan secara
horizontal ( tidak memandang perbedaan lapisan). Diferensiasi
digolongkan atas: jenis kelamin, agama,
profesi, klan, suku bangsa, asal daerah dan ras
a.
Ciri
fisik (ras, jenis kelamin)
b.
Ciri
sosial (profesi, peran di masyarakat)
c.
Ciri
budaya (pandangan hidup, religi, sistem
kekeluargaan, klan, norma dan nilai yang dianut).
2.
Stratifikasi
Sosial
Merupakan pembedaan
penduduk atau masyarakat ke dalam kelas
– kelas secara bertingkat (hierarkhis/vertikal
).
a.
Dasar untuk
menggolangkan pelapisan sosial
1)
Kekayaan
Kekayaan adalah kriteria
ekonomi, maka orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau besar akan menempati
lapisan sosial yang tinggi pula
2)
Kekuasaan (Power)
Orang-orang yang memperoleh kesempatan
menjadi pemimpin, baik melalui suatu mekanisme pemilihan umum maupun secara
turun temurun (pada negara sistem monarki), akan menempati kelas sosial yang
lebih tinggi.
3)
Kehormatan
Golongan
bangsawan, baik pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern,
selalu menduduki kelas sosial yang lebih tinggi. Mereka sangat dihormati,
bahkan sering dijadikan sumber dari berbagai kebutuhan sosial manusia. Biasanya
keturunan kelas bangsawan ini akan secara otomatis menjadi orang yang berada
dan menyandang status sosial orang tuanya tersebut.
4)
Pendidikan
Pada masyarakat yang mulai berkembang atau
masyarakat pra industri, pendidikan menjadi suatu yang amat penting, sehingga
orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi secara otomatis akan menempati
lapisan sosial yang tinggi pula. Mislanya, kelompok sarjana di negara manapun
mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang hanya
menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan kejuruan.
b.
Bentuk Stratifikasi
Sosial
1)
Kriteria
Ekonomi
Kriteria ekonomi
masyarakat dibedakan menurut penguasaan materi dan sumber daya.
 |
| Kriteria Ekomoni (Aristoteles) |
 |
| Kriteria Ekonomi (Secara Umum) |
 |
| Kriteria Ekonomi Penguasaan Sumber daya (masyarakat demokratis) |
2)
Kriteria
Politik
a)
Kasta
Tipe
kasta adalah tipe atau sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang
tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta
yang hampir tidak terjadi mobilitas sosial vertikal. Garis pemisah antara
masing-masing lapisan hampir tidak mungkin ditembus.
 |
| Stratifikasi tipe kasta |
b)
Oligarkis
Tipe
ini memiliki garis pemisah yang tegas, tetapi dasar pembedaan kelas-kelas
sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Tipe ini hampir sama
dengan tipe kasta, namun individu masih diberi kesempatan untuk naik
lapisan.
 |
| Stratifikasi tipe Oligarkis |
c)
Demokratis
Tipe
ini menunjukkan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil
(bergerak) sekali. Dalam hal ini kelahiran tidak menentukan kedudukan
seseorang, melainkan yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang
faktor keberuntungan.
c.
Sifat Struktur
Sosial
1)
Tertutup
Pada sistem stratifikasi sosial tertutup (closed
stratification), terdapat pembatasan terhadap kemungkinan pindahnya
kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Jadi, dalam
sistem stratifikasi sosial tertutup bersifat tetap. Satu-satunya jalan supaya
berada pada suatu lapisan kelas tertentu adalah melalui kelahiran. Pada
stratifikasi ini gerak sosial tidak dapat terjadi karena seseorang tidak dapat
naik, atau bahkan turun ke kelas sosial lainnya.
 |
| Stratifikasi Sosial Tertutup |
2)
Terbuka
Di dalam stratifikasi sosial terbuka (open
stratification), kelas-kelas sosial tidak bersifat tertutup, artinya
seseorang dapat saja masuk ke dalam kelas sosial tertentu yang diinginkan
ataupun keluar setelah mencapai kelas sosial yang lebih tinggi. Seseorang dapat
pula ‘dikeluarkan” apabila tidak sanggup melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
sesuai dengan kelas sosial yang disandangnya. Sistem kelas sosial terbuka
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha dengan kemampuannya
sendiri masuk ke kelas tertentu.
 |
| Stratifikasi Terbuka |
3)
Campuran
Mobilitas
terjadi secara bebas, namun ada posisi yang tidak dapat berubah. Posisi sosial tersebut
dapat diperoleh melalui perjuangan dan ditentukan oleh garis keturunan Contoh:
seseorang menganut kasta brahmana (kedudukan tinggi), namun karena sistem yang
dianut oleh masyarakat merupakan demokratis, jadi orang tersebut harus menyesuaikannya.
 |
| Stratifikasi Sosial Campuran |
E.
Perkembangan Struktur Sosial Masyarakat
Selo Sumardjan membagi
perkembangan struktur social masyarakat menjadi tiga bentuk
1. Masyarakat sederhana
a. Memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun
temurun
b. Memiliki ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat
c. Mengedepankan system gotong royong
d. Menerapkan system hokum tidak tertulis
e. Masih memiliki kepercayaan pada kekuatn ghoib
f. Hasil produksi tidak untuk dijual ,tetapi untuk
dikonsumsi sendiri
2. Masyarakat madya
a. Intensitas ikatan kekeluargaan tidak seerat
masyarakat sederhana
b. Lebih terbuka dengan perubahan social
c. Menerapkan system hokum tertulis dan tidak tertulis
d. Mulai membentuk lembaga formal
e. Mulai muncul pemikiran rasionalitas meskipun tetap
mempercayai adanya kekuatan ghaib
f. Mulai mengenal system diferensiasi social dan
stratifikasi sosial
3. Masyarakat modern
a. Hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi
b. Membentuk hubungan sosial yang bersifat terbuka
c. Mengembangkan pola pikir positivis
d. Masyarakat punya tingkat ilmu pengetahuan yang
tinggi
e. Memberlakukan system hokum formal atau tertulis
f. Membentuk stratifikasi sosial berdasarkan pada
keahlian

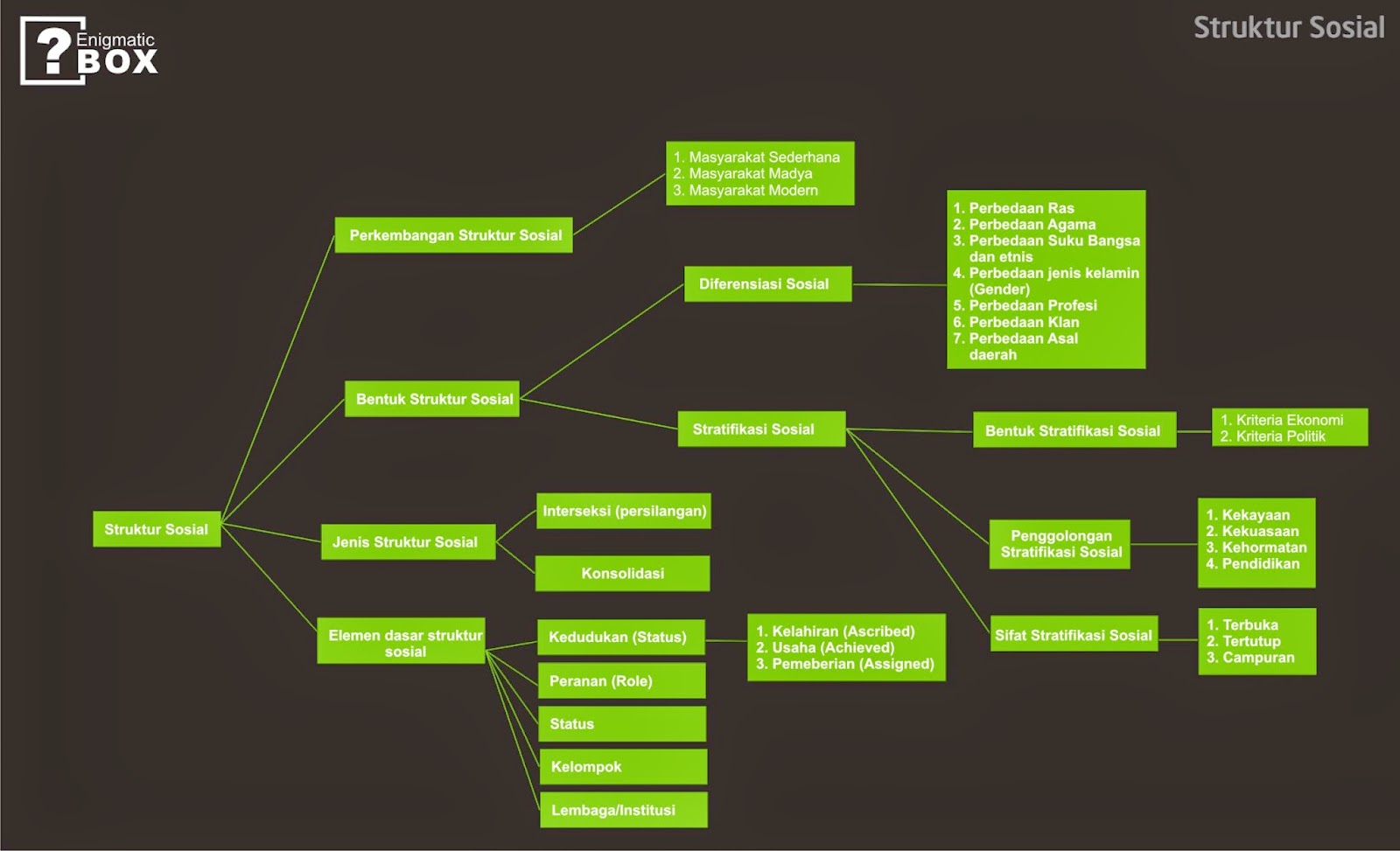

Tidak ada komentar:
Posting Komentar